sukabumiheadline.com – Kuatnya budaya feodalisme menunjukan arah bagaimana pada akhirnya peran wanita ditentukan oleh “budaya” yang kuat mengakar dalam kehidupan sehari-hari yang dialami wanita Sukabumi.
Pengaruh ini tetap berkembang meskipun kolonialisme sudah masuk sejak puluhan tahun sebelumnya, namun mengingat para kolonialis tetap menggunakan pembesar lokal untuk menjadi kepanjangan tangannya hingga mereka pun menyerap budaya feodalisme ke dalam budaya indies. Meskipun pada awalnya masih terkesan kikuk.
Kisah tragis Apun Geuncay dari Cikembar yang hendak dijadikan selir oleh Bupati Cianjur Wiratanudatar III menegaskan kuatnya feodalisme di Sukabumi kala itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wanita merupakan makhluk istimewa, dan terbukti sejarah telah banyak mencatatnya. Tidak terkecuali di Sukabumi. Meskipun secara fisik dan emosi memiliki perbedaan dengan pria, namun wanita Sukabumi memegang peran penting dalam banyak catatan sejarah.
Persepsi alam dan budaya secara universal menempatkan wanita dalam konotasi alam, tanah, dan ladang. Sedangkan pria dikonotasikan sebagai pacul atau benih. Pola pelabelan ini menempatkan wanita sebagai objek budaya, jika wanita adalah alam, maka laki-laki adalah budaya yang mengolahnya.
Feodalisme dalam masyarakat Sukabumi yang dipengaruhi budaya Mataram, menguatkan persepsi masyarakat yang selalu menempatkan wanita sebagai subordinasi kaum Adam. Mirisnya, budaya patriarki¹ kian melanggengkannya.
(1) Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Dalam domain keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda.
Berikut adalah ulasan fenomena Nyai dan masa kegelapan wanita Sukabumi pada masa kolonial Belanda hingga Jepang, disarikan dari jaringan sukabumiheadline.com, sukabumixyz.com.
Lembaga pernikahan tak mengubah budaya feodal dan patriarki
Meskipun ada sebagian yang kemudian disahkan melalui pernikahan resmi, bahkan ada pula yang diakui keturunannya, namun kebanyakan hanya menjadi ‘alas tidur’ tuan perkebunan. Dalam situasi ini konsep-konsep feodal kemudian dimunculkan dengan interpretasi keliru, seperti ungkapan taraje nandeuh dulang tinande yang mencerminkan kepatuhan total wanita terhadap laki-laki.
Nyai, bukanlah istri seutuhnya tetapi pembantu yang serba bisa, bisa mengurus rumah, memasak, mencuci, mengurus anak-anak sekaligus mengurus ‘kebutuhan’ tuannya. Maka tak heran jika sampai saat ini, persepsi bahwa urusan wanita hanya berkutat di sumur, dapur dan kasur, tetap terpelihara.
Dalam kisah Nyai Komot dari perkebunan Simpenan, sang Nyai bahkan melayani hingga melahirkan dan hingga sang Tuan August de Groot tiada. Anak-anaknya Nyai kemudian pergi ke Belanda meninggalkan dirinya.
Tak kalah menyedihkan, kisah tragis nyai Belanda di Parungkuda, Nyai Asmanah yang merasa kecewa karena tuannya (van Doorman) mengambil Nyai lain, hingga akhirnya Asmanah memilih membunuh van Doorman karena dibakar api cemburu.
Kisah ini sempat ramai di media masa Eropa hingga diangkat menjadi sebuah novel berjudul Hikajat Pemboenoehan Doorman.
Kisah hebat wanita Sukabumi yang disembunyikan
Sebenarnya ada kisah wanita Sukabumi seperti yang dicatat Clockener Brousson tahun 1901 mengenai Maridjah yang pandai berbahasa Belanda, putri seorang Patih Sukabumi. Gadis yang dipanggil Maria oleh orang Belanda ini memiliki sikap egaliter dan dihormati banyak kalangan.
Namun, kisah Maria ini seperti sengaja disembunyikan agar budaya feodalisme, dan patriarki yang menempatkan wanita sebagai subordinasi kaum Adam, tetap terpelihara.
Menjadi objek seksisme dalam masa kolonial
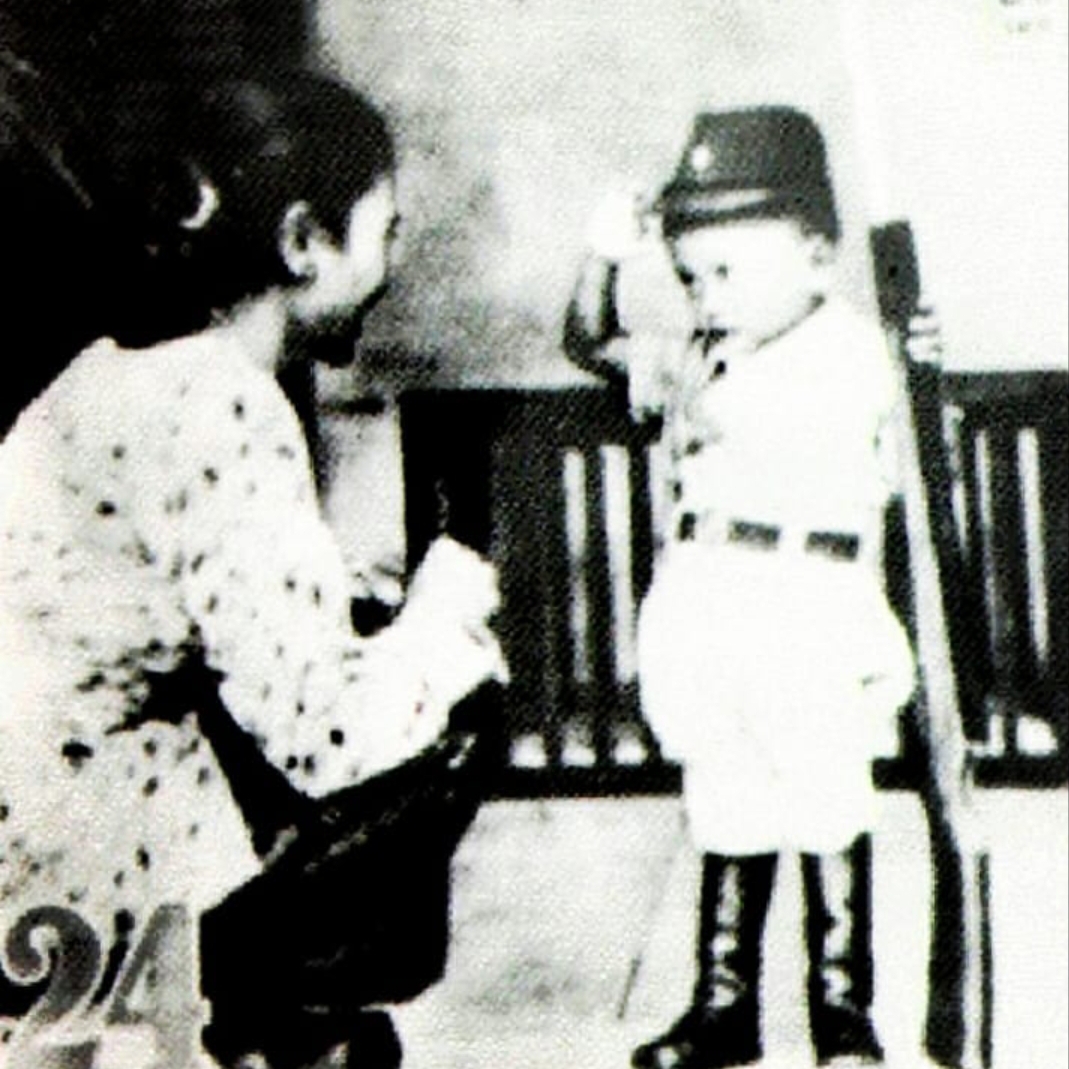
Persoalan Nyai yang masih dalam kategori samar semakin terbuka dengan munculnya para orientalis dan fotografer yang cenderung menjadikan mereka sebagai objek. Sebagian orientalis terobsesi dengan eksotisme timur seperti yang menjadi pembicaraan-pembicaraan para traveller, mirip gambaran kritikus sastra Edward Said yang disebut sebagai keserbalainan, kemewahannya yang dicemburui, termasuk imajinasi-imajinasi nakal tentang timur yang dianggap telanjang.
Pada akhirnya produksi foto-foto setengah telanjang yang sebagian di-setting terutama di Tatar Sunda, kemudian dipublikasikan di Belanda bahkan dipamerkan dalam persmian menara Eiffel.
Padahal, dalam budaya Sunda tidak diperbolehkan memperlihatkan bagian tertentu, misalnya dalam téks Carita Radén Jayakeling (Kropak 407) disebutkan “pinareup mangka abenan, mulah dimangka cugenang” (buah dada tutuplah dengan aben, jangan dibiarkan menyembul).
Perempuan harus senantiasa menutupi payudaranya dengan aben yang memiliki fungsi yang sama dengan bra. Bahkan rambut tidak boleh sehelaipun dibiarkan tergerai dengan kalimat ‘mulah dimangka ngarunday’.
Kemungkinan foto-foto setengah telanjang wanita Sunda tersebut memang diatur demikian oleh sang fotografer untuk menarik pembeli, karena tidak mencerminkan budaya asli Sunda.
Objek seksualitas dalam masa kolonial
Situasi ini menjadi kian parah saat kolonialis Jepang masuk ke Sukabumi. Seperti yang dilakukan Jepang di wilayah lain, di Sukabumi juga muncul praktik Jugun Ianfu, yaitu perempuan muda yang dijadikan sebagai budak seks para tentara Jepang.
Mereka dikumpulkan di rumah-rumah bekas Belanda, di antaranya yang tercatat adalah rumah bekas Tuan Kipers (sekarang Gedung Inspektorat Kota Sukabumi, dan di Gedung Panjang Baros). Mereka yang dirasa masih muda dan menarik, diambil paksa dari desa-desa maupun kota di Sukabumi. Mereka diminta langsung kepada orangtuanya dengan iming-iming dipekerjakan, hingga dibiayai sekolah.
Pada kenyataannya mereka dikumpulkan di rumah-rumah bordil yang disebut Ianjo. Tempat tersebut dijaga ketat bala tentara Jepang. Jumlah perempuan yang berada di dalam rumah itu bisa mencapai 30 hingga 50 orang. Mereka semua ‘bekerja’ pada malam hari untuk melayani para tentara Jepang di bawah ancaman.
Tempat pengepulan perempuan-perempuan itu anatara lain berada di Perbawati, Goalpara, Sukaraja, dan Ciengang, Kabupaten Sukabumi sekarang. Mereka diperkosa di penginapan-penginapan kecil di sekitar Kebon Cau. Data yang pernah dihimpun, ada sekitar 818 orang wanita Jugun Ianfu di Sukabumi. Ini tidak termasuk Jugun Ianfu dari wilayah Sukabumi lainnya.
Pola ekspolitasi wanita oleh kolonialis kemudian berakhir saat Indonesia merdeka, bangsa kita kembali memuliakan perempuan, dan terbukti dengan munculnya kalangan wanita dalam dunia politik, baik di eksekuyif maupun legislatif di Sukabumi.
Dilarang republikasi artikel kategori Headline dan Rubrik Headline tanpa seizin Redaksi sukabumiheadline.com
Artikel ini disarikan dari media jaringan sukabumiheadline.com dengan judul asli: Wanita Sukabumi (part 2): Dari objek seksisme hingga kisah hebat yang disembunyikan















